PIK 2, Ketika Pembangunan Lupa pada Keadilan Sosial
“Pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara yang lainnya terpinggirkan, bukanlah kemajuan. Itu cuma ilusi, sebuah jalan yang tidak jelas arahnya.”
Bung Eko Supriatno
David Harvey, dalam bukunya Social Justice and the City (1973), menegaskan bahwa geografi perkotaan tidak dapat dipisahkan dari keberpihakan terhadap keadilan sosial. Ketika kemiskinan dan ketidakadilan merajalela di ruang kota, geografi bukan sekadar ilmu yang netral, melainkan alat untuk mengurai dinamika kekuasaan dan ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila menuntut agar setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan politik.[1] Namun, di balik megahnya proyek pembangunan seperti Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), pertanyaan besar muncul: siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Dualitas Sosial di Tengah Kemewahan
PIK 2 berdiri sebagai simbol modernitas: sebuah kawasan elite dengan infrastruktur mewah, akses mudah, dan janji gaya hidup ramah lingkungan. Namun, hanya beberapa kilometer dari kemewahan itu, terdapat Desa Tegalangus, potret nyata dari ketimpangan sosial. Desa ini sering dilanda banjir, masalah yang berakar pada minimnya sistem drainase yang memadai, diperburuk oleh dampak pembangunan skala besar di sekitarnya.[2]
Dualitas ini menggambarkan jurang tajam antara mereka yang menikmati hasil pembangunan dan mereka yang menanggung dampaknya. Bagi penghuni kawasan elite, PIK 2 adalah surga investasi.
Tetapi bagi masyarakat Tegalangus, setiap hujan deras membawa ancaman banjir yang merusak rumah dan mata pencaharian mereka.[3]
Janji Proyek Nasional, Beban Warga Lokal
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), PIK 2 didesain untuk menarik investasi besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti banyak proyek berskala nasional lainnya, dampaknya terhadap masyarakat sekitar sering kali diabaikan.
Jalanan licin, gedung pencakar langit, dan taman hijau yang dirancang untuk para penghuni elite justru menjadi saksi bisu penderitaan masyarakat kecil yang terpinggirkan.
Apakah keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan pembangunan telah menjadi jargon kosong?
Desa Tegalangus adalah pengingat bahwa pembangunan tanpa pemerataan adalah pembangunan yang pincang. Banjir yang kerap melanda desa ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan hasil dari kegagalan sistemik dalam merancang infrastruktur yang inklusif.
Tegalangus adalah contoh kecil dari ironi besar: pembangunan yang disebut-sebut membawa kemajuan justru menciptakan luka baru bagi masyarakat di sekitarnya.
Membangun dengan Hati, Bukan Hanya Modal
Keadilan sosial tidak sekadar berbicara tentang angka atau investasi; ini adalah soal keberpihakan. Ketika sebuah proyek sebesar PIK 2 dirancang, apakah aspirasi masyarakat lokal didengar? Apakah kebutuhan mereka menjadi bagian dari perencanaan?
Di sinilah pentingnya pendekatan pembangunan yang memanusiakan. Keadilan sosial harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar slogan. Tanpa itu, pembangunan hanya akan melahirkan kota-kota gemerlap yang dikelilingi oleh penderitaan.
Sebagai sebuah bangsa, kita harus berani menantang pola pikir pembangunan yang hanya melayani segelintir orang. PIK 2 bisa menjadi simbol kemajuan yang sejati jika keberpihakan terhadap masyarakat kecil, seperti warga Tegalangus, diwujudkan.
Pada akhirnya, seperti yang diingatkan oleh David Harvey, geografi perkotaan adalah refleksi dari siapa yang memegang kendali atas ruang dan sumber daya. Jika kendali itu hanya ada di tangan segelintir elite, maka keadilan sosial akan tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.
Inklusivitas dan Konsep Eco-City di PIK 2
Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), PIK 2 Tropical Coastland berupaya menampilkan wajah modern dengan konsep eco-city yang ramah lingkungan dan kawasan hijau berkelanjutan. Dengan investasi sebesar Rp 39 triliun, proyek ini diharapkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja, memberikan dampak ekonomi luas, dan memperkuat posisi Indonesia di peta investasi internasional.
Meski sepenuhnya didanai oleh swasta tanpa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan dukungan regulasi. Fasilitas publik seperti masjid dan gereja juga dibangun sebagai bentuk integrasi sosial dan untuk meredam kritik masyarakat terhadap proyek ini. Di sisi lain, pengembang turut menyediakan bantuan berupa pompa banjir dan perawatannya bagi desa-desa sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
Namun, langkah ini dinilai banyak pihak belum cukup menyelesaikan persoalan mendasar. Sistem drainase yang buruk di kawasan sekitar masih menjadi sumber utama banjir, sementara perubahan fungsi lahan perlahan mengikis identitas lokal dan tradisi warga desa.
Kekhawatiran atas hilangnya masjid kecil, mushola, serta ruang-ruang komunitas agama menjadi isu yang mengemuka.[4]
Kontroversi, Konflik Agraria, dan Tuntutan Keadilan
Di balik gemerlapnya proyek PIK 2, konflik agraria menjadi noda yang sulit diabaikan. Masyarakat lokal, termasuk ulama dan pemilik lahan lama, kerap menolak proyek ini karena menilai adanya praktik perampasan tanah untuk kepentingan bisnis properti. Tuduhan kriminalisasi terhadap pemilik tanah asli, yang melibatkan pengembang besar seperti Agung Sedayu Group, semakin memperkuat narasi ketidakadilan dalam pelaksanaan PSN ini.
Proses perizinan yang dianggap belum tuntas juga menjadi sorotan, dengan kritik bahwa pelaksanaan proyek lebih menguntungkan oligarki dibanding memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Selain itu, kekhawatiran atas hilangnya tradisi lokal akibat perubahan fungsi lahan menjadi kawasan elite semakin memperdalam jurang ketidakpuasan masyarakat sekitar.
Pemerintah diharapkan mengambil peran aktif dalam memastikan keadilan sosial bagi warga terdampak. Mediasi konflik agraria, evaluasi mendalam terhadap status PSN, dan kebijakan pembangunan yang inklusif adalah langkah penting yang perlu diambil. Langkah revitalisasi mangrove di area proyek juga harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
Pada akhirnya, pembangunan kawasan elite seperti PIK 2 seharusnya tidak menjadi simbol kesenjangan sosial, melainkan mencerminkan keberpihakan terhadap kesejahteraan bersama. Keberhasilan proyek ini hanya dapat diukur jika keadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat kecil di sekitarnya, dapat diwujudkan.
Partisipasi Publik untuk Keadilan Pembangunan
Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2 membawa janji besar, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga modernisasi kawasan. Namun, janji ini sering kali berhadapan dengan realitas kompleks di lapangan. Ketidakhadiran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sering menjadi akar ketegangan sosial yang sulit diurai.
Sejatinya, partisipasi publik bukan sekadar formalitas. Ini adalah instrumen penting untuk menciptakan harmoni antara ambisi pembangunan dan kebutuhan lokal. Dalam kasus PIK 2, masyarakat sekitar, seperti warga Desa Tegalangus yang sering terdampak banjir, harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan. Aspirasi mereka tidak hanya relevan, tetapi juga vital dalam memastikan bahwa pembangunan ini tidak menciptakan jurang ketimpangan baru.[5]
Mengapa Partisipasi Publik Penting?
Keterlibatan masyarakat dalam proyek besar seperti PIK 2 adalah kunci menciptakan harmoni antara pembangunan dan kebutuhan lokal. Proses ini memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, memberikan ruang bagi warga untuk mengetahui rencana pembangunan, potensi dampaknya, dan langkah mitigasi yang akan dilakukan. Dengan demikian, kecurigaan atau asumsi negatif dapat diminimalkan sejak awal.
Lebih dari sekadar infrastruktur, proyek ini memengaruhi ruang hidup, identitas budaya, dan tradisi lokal. Dialog yang terbuka antara pengembang dan masyarakat dapat menjembatani visi besar proyek dengan kebutuhan komunitas sekitar. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan juga membantu mencegah konflik,[6] khususnya agraria, yang sering muncul dalam proyek berskala besar.
Kejelasan tentang status lahan, kompensasi yang adil, dan solusi bagi warga terdampak menjadi elemen penting untuk menjaga hubungan harmonis.
Partisipasi publik juga menciptakan rasa memiliki. Ketika warga dilibatkan, mereka tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari perubahan yang terjadi. Rasa memiliki ini memperkuat dukungan sosial terhadap proyek sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan.
Untuk mencapai hal ini, forum diskusi terbuka harus menjadi ruang yang inklusif, tempat warga bebas menyampaikan pandangan dan kritik. Kajian dampak sosial yang komprehensif perlu dilakukan sejak awal untuk memastikan semua langkah pembangunan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Tim mediasi independen yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi bisa menjadi penengah antara pengembang dan warga, memastikan janji-janji proyek benar-benar diwujudkan.
Kompensasi yang adil juga merupakan keharusan. Warga terdampak harus menerima ganti rugi yang setimpal, baik dalam bentuk finansial maupun infrastruktur pengganti yang layak. Semua komitmen ini harus dituangkan dalam dokumen hukum yang transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Selain itu, program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan dapat menjadi langkah preventif terhadap ketidakadilan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya soal memenuhi prosedur administratif, tetapi investasi sosial untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
Proyek PIK 2 memiliki peluang besar menjadi simbol kemajuan yang inklusif, asalkan suara masyarakat benar-benar didengar dan diwujudkan. Dengan mengutamakan partisipasi publik sebagai pilar utama, pembangunan akan membawa manfaat ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial, menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Tentang penulis: BUNG EKO SUPRIATNO (Dosen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas. Mathla’ul Anwar
DAFTAR PUSTAKA
Buku
- Harvey, D. (2012). Kota Pemberontak: Dari Hak atas Kota Menuju Revolusi Perkotaan. Verso.
Jurnal dan Artikel
- Ananta, DD. (2012). Partisipasi Masyarakat dan Hak Atas Kota: Review atas Pemikiran David Harvey. Diakses dari http://pergerakan.org/partisipasi-masyarakat-dan-hak-atas-kota-review-atas-pemikiran-david-harvey/
- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. Jurnal Dekonstruksi, 3(1), 1-12. ISSN 2797-233X. Diakses dari https://dekonstruksi.id/index.php/home/issue/view/
- Teori Ketimpangan Pembangunan Geografis David Harvey dalam Tinjauan Filsafat Ekonomi. (n.d.). Diakses dari https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/216168
Lembaga dan Organisasi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. (n.d.). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Feodalisme Picu Revolusi Sosial Banyuwangi. Diakses dari https://fisipol.ugm.ac.id/konflik-agraria-dan-ketimpangan-struktur-feodalisme-picu-revolusi-sosial-banyuwangi/
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (n.d.). Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Diakses dari https://law.ugm.ac.id
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr
Opini dan Media
- Kompas. (2024). Kebijakan Pertanahan dan Keadilan Sosial. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/24/kebijakan-pertanahan-dan-keadilan-sosial
Organisasi Bantuan Hukum
- LBH Jakarta & KontraS. (2024). Proyek Strategis (baca: Sengsara) Nasional Menimbulkan Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM: Pembangunan PIK 2 Harus Dihentikan, Cabut Status PSN-nya! Siaran Pers, 7 November 2024. Diakses dari https://bantuanhukum.or.id/proyek-strategis-baca-sengsara-nasional-menimbulkan-konflik-sosial-dan-pelanggaran-ham-pembangunan-pik-2-harus-dihentikan-cabut-status-psn-nya/
Esai dan Refleksi
- Anshori, AG. (n.d.). Keadilan Sosial Sebuah Paradigma Pendekatan Pembangunan – Keadilan Dalam Konteks Perkembangan Paradigma. Diakses dari https://br.mmexpress.org/paradigma/keadilan-dalam-konteks-perkembangan-paradigma-2846684
- Kurniawan, R. (n.d.). David Harvey (Hak Atas Kota). Diakses dari https://www.academia.edu/8813903/DAVID_HARVEY_Hak_Atas_Kota
[1]David Harvey dalam Social Justice and the City (1973) menekankan geografi perkotaan sebagai alat memahami kekuasaan dan ketimpangan sosial, relevan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila (Harvey, 2012). Harvey, D. (2012). Kota Pemberontak: Dari Hak atas Kota Menuju Revolusi Perkotaan. Verso.
[2] LBH Jakarta & KontraS. (2024). Proyek Strategis (baca: Sengsara) Nasional Menimbulkan Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM: Pembangunan PIK 2 Harus Dihentikan, Cabut Status PSN-nya! Siaran Pers, 7 November 2024. Diakses dari https://bantuanhukum.or.id/proyek-strategis-baca-sengsara-nasional-menimbulkan-konflik-sosial-dan-pelanggaran-ham-pembangunan-pik-2-harus-dihentikan-cabut-status-psn-nya/
[3] Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. Jurnal Dekonstruksi, 3(1), 1-12. ISSN 2797-233X. Diakses dari https://dekonstruksi.id/index.php/home/issue/view/
[4] Konsep eco-city PIK 2 sering mengabaikan identitas lokal dan kebutuhan masyarakat, menunjukkan kelemahan dalam pelibatan komunitas (Kementerian Kominfo RI, n.d.). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr
[5] Partisipasi publik inklusif, sebagaimana ditegaskan Harvey, diperlukan untuk mengurangi konflik sosial dan memastikan keadilan pembangunan (Ananta, 2012). Ananta, DD. (2012). Partisipasi Masyarakat dan Hak Atas Kota: Review atas Pemikiran David Harvey. Diakses dari http://pergerakan.org/partisipasi-masyarakat-dan-hak-atas-kota-review-atas-pemikiran-david-harvey/
[6] Konflik agraria pada proyek PIK 2 menggarisbawahi pentingnya mediasi dan evaluasi kebijakan untuk menjamin keadilan sosial (FISIP UGM, n.d.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. (n.d.). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Feodalisme Picu Revolusi Sosial Banyuwangi. Diakses dari https://fisipol.ugm.ac.id/konflik-agraria-dan-ketimpangan-struktur-feodalisme-picu-revolusi-sosial-banyuwangi/







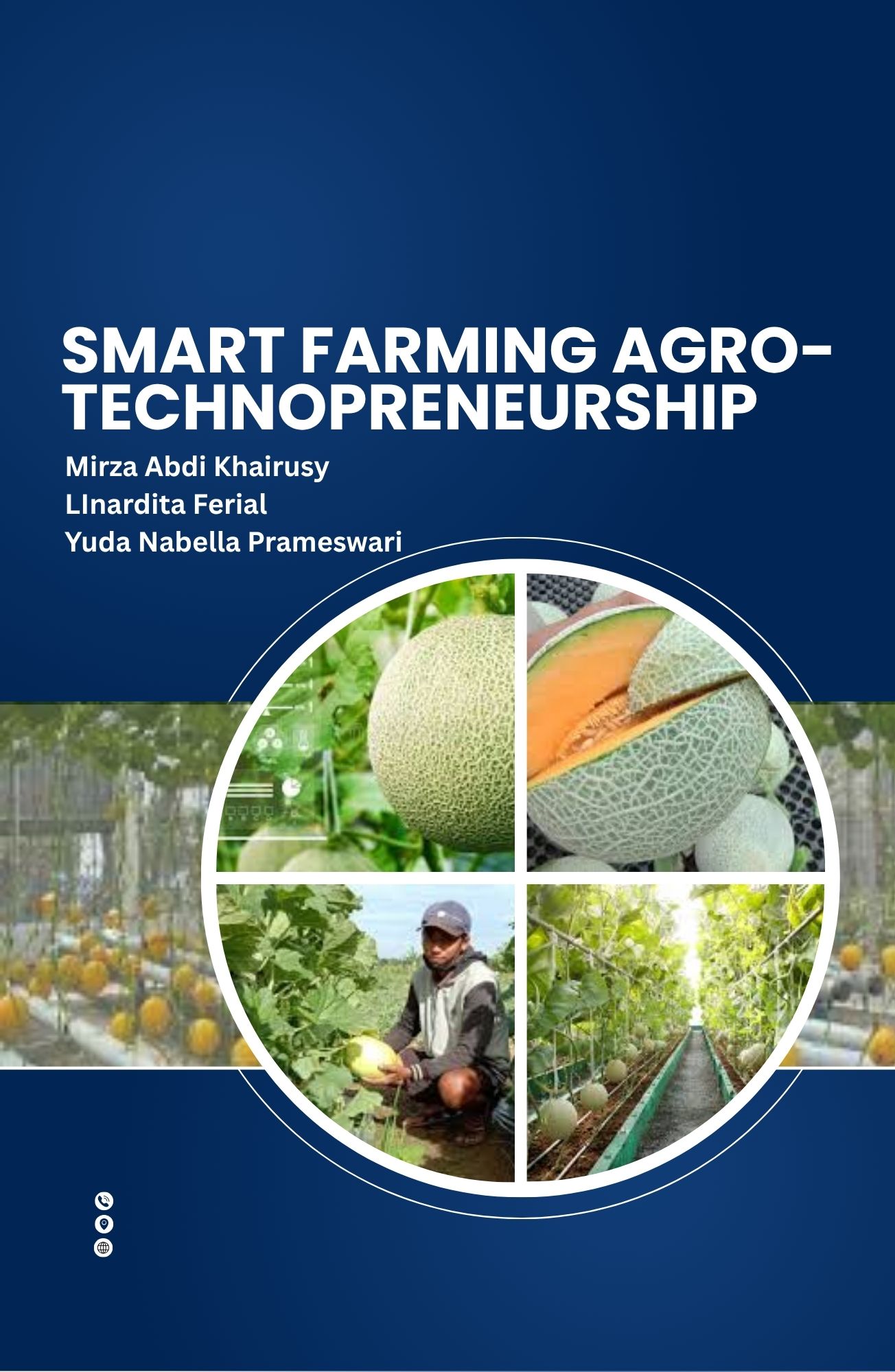


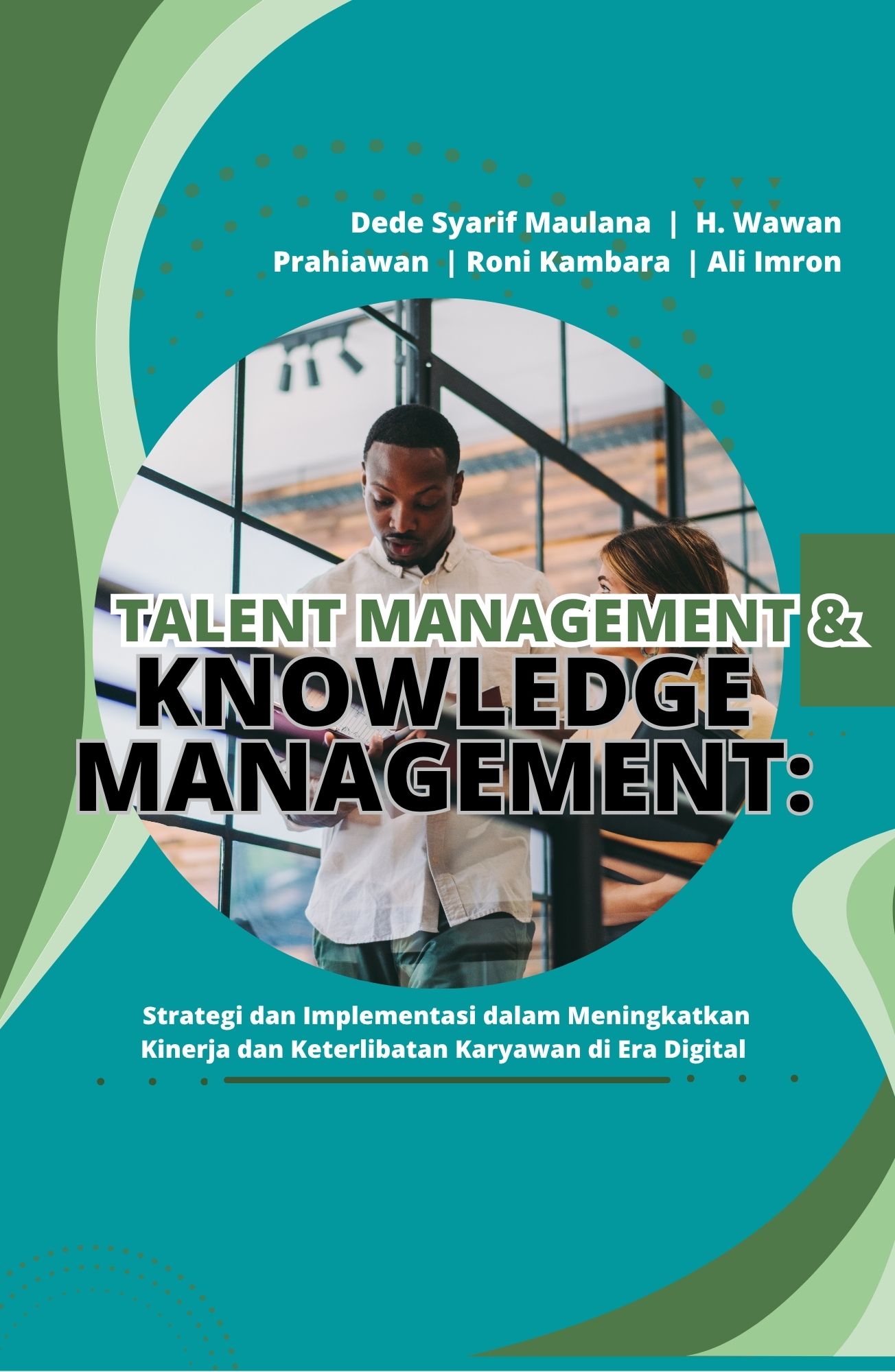
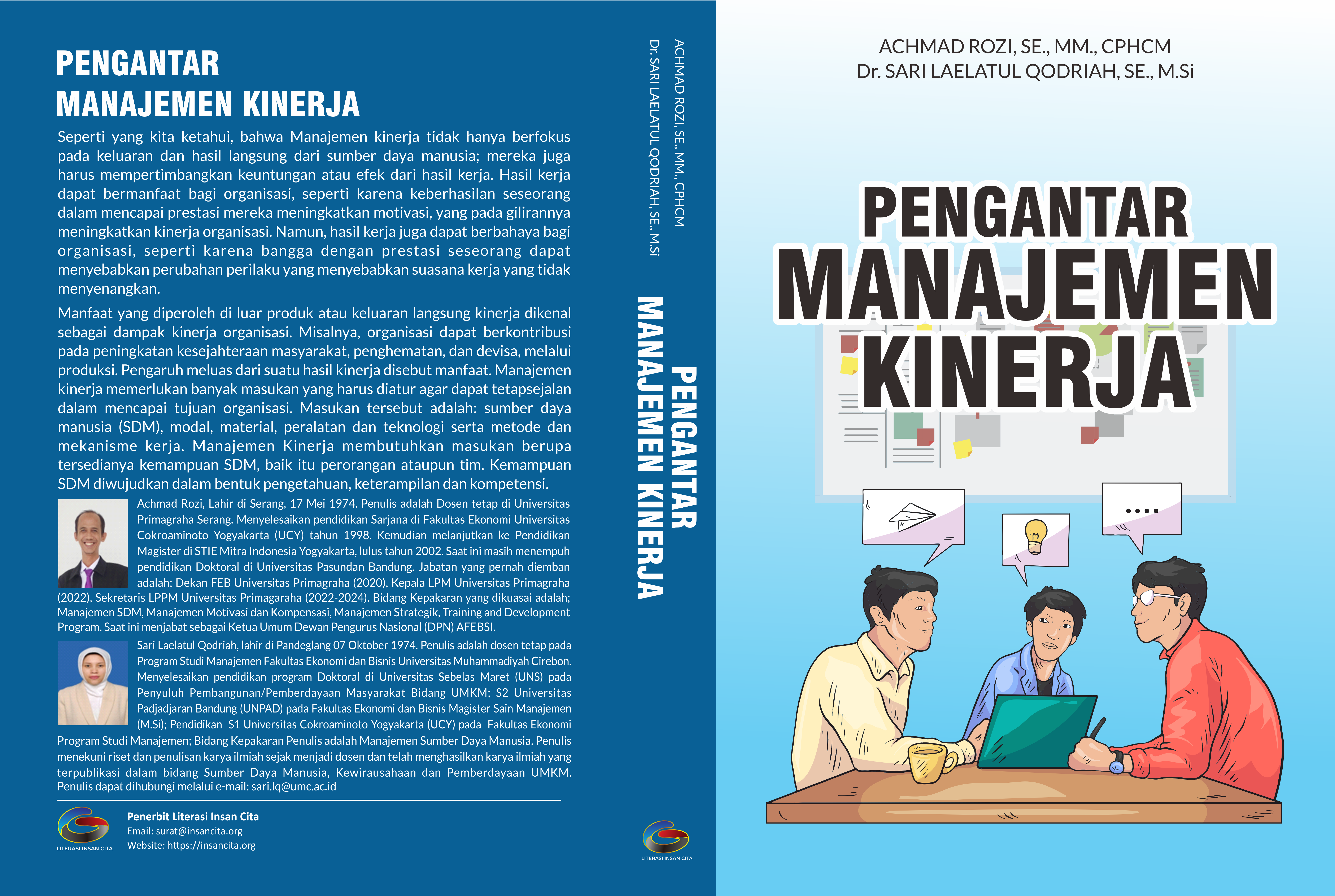
Tinggalkan Balasan